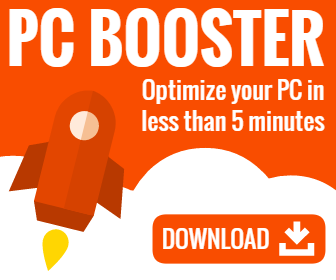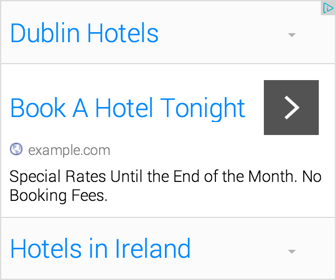JurnalPost.com – Psikolog sosial dari Holland Hofstede (1980) menemukan bahwa 80% penduduk dunia hidup dalam ketergantungan pada orang lain, dengan kata lain identitasnya ditentukan oleh faktor eksternal, kelompok tertentu, tentu saja dapat terjerumus dalam budaya kolektivisme. yang berarti lebih menekankan pada kepentingan kelompok. Markus dan Kitayama (1990) mengistilahkan budaya kolektivis sebagai pandangan saling bergantung terhadap diri sendiri yang mencakup identitas seseorang yang ditentukan oleh peran dan keanggotaan kelompok. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Apa mekanisme yang mendasari pandangan saling ketergantungan terhadap diri sendiri atau budaya kolektivis ini? Apa pendahulu dari pandangan saling ketergantungan tentang diri atau budaya kolektivis ini? Dan jika dikonseptualisasikan dan didefinisikan, lalu apa nama lain dari pandangan saling ketergantungan tentang diri atau budaya kolektivis ini? Dan dalam budaya manakah kita dapat menemukan fenomena pandangan diri yang saling bergantung atau budaya kolektivis?
Takeo Doi, seorang psikoanalis dari Jepang, menyebut konsep lain dari pandangan diri yang saling bergantung sebagai amae dalam bukunya Anatomy of Addiction. Amae diambil dari kamus bahasa Jepang yang artinya manis, sedangkan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bisa berarti main-main atau kekanak-kanakan, artinya bermain atau bertingkah seperti bayi. Mentalitas amae didefinisikan sebagai upaya untuk menyangkal fakta pemisahan, yang merupakan bagian integral dari keberadaan manusia, dan untuk menghilangkan rasa sakit, karena pemisahan dan amae telah dianggap sebagai aspek fundamental dalam psikologi rakyat Jepang sejak dahulu kala (Doi, 1973). Behrens (2004) juga menambahkan bahwa amae dapat digambarkan sebagai sebuah konsep yang berasal dari penduduk asli Jepang mengenai keterhubungan. Doi (1973) menekankan hubungan ibu-bayi sebagai prototipe hubungan amae sepanjang hidup seseorang, menambahkan bahwa amae menumbuhkan rasa persatuan antara ibu dan anak.
Taketomo (1986) melengkapi dan menambah literatur Doi (1973) bahwa Doi tidak memiliki mekanisme metakomunikasi dari amae itu sendiri, yang mana Taketomo mengungkapkan bahwa terdapat mekanisme amaeru dan amayakasu dalam amae. Ketika anak dengan bercanda meniru tingkah laku anak, maka anak tersebut bukanlah anak kecil, demikian kata Doi. Namun dengan perilaku tersebut, anak berusaha berkomunikasi dengan ibunya bahwa ia menginginkan amaera dan ingin ibunya melakukan amayakasa untuknya. Taketomo sependapat dengan Doi bahwa amae yang memiliki unsur kekanak-kanakan merupakan prototipe, namun Taketomo lebih fokus pada fenomena amae yang terjadi pada masa kanak-kanak dan dewasa, bukan hanya pada masa bayi. Contoh masa dewasa yang digambarkan Taketomo adalah ketika seorang wanita dewasa berperilaku main-main seperti bayi.
Maruta (1992) berpendapat dan mengkritik Doi bahwa Doi hanya fokus pada anak yang menginginkan amaera dan mengabaikan peran ibu yang menginginkan amayakasa. Anak atau ibu mungkin memulai proses amae untuk memulihkan keintiman atau rasa aman. Maruta mengatakan, amae yang sukses adalah ketika menciptakan kenikmatan bagi kedua belah pihak, menciptakan rasa nyaman bersama di antara kedua belah pihak. Maruta menambahkan, mempelajari sesuatu yang membuat nyaman bersama merupakan bagian penting untuk tumbuh dan berkembang agar bisa bertahan di Jepang, tentunya dapat dikatakan bagian dari budaya Jepang karena berkaitan dengan definisi operasional budaya yaitu “ cara kita melakukan sesuatu di sini dan saat ini.”
Watanabe (1992) berpendapat bahwa ketika seorang ibu melakukan amayakasa kepada anaknya dan hasilnya memenuhi kebutuhan anak maka hal ini dapat bermanfaat bagi anak karena anak akan merasa aman. Namun, bisa berbahaya dan tidak nyaman bagi anak bila ibu melakukan amayakasa untuk memenuhi kebutuhan ego ibu. Watanabe membedakan antara amae yang terjadi pada masa kanak-kanak dan amae yang terjadi pada orang dewasa, yaitu ekspektasi dan ikatan sosial harus dipenuhi agar amae dapat terwujud.
Melalui tinjauannya tentang amae, Johnson (1993) mengemukakan beberapa poin penting bahwa amae lebih luas daripada hubungan ketergantungan atau interdependen. Amae mengidentifikasi Doi sebagai dorongan, keinginan, atau motif yang mendasari manusia. Amae mewakili ekspresi budaya Jepang tentang ketergantungan yang memanjakan diri sendiri, dan versi lain dari dinamika ini umumnya memiliki bentuk yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Ketergantungan dan saling ketergantungan dalam konteks amae dapat diamati sepanjang hidup seseorang. Amae bukanlah fenomena sederhana karena dapat diselidiki melalui berbagai tingkat pengalaman subjektif dan perilaku subjektif seseorang. Tentunya dari hasil kajian komprehensif Johnson (1993), dapat dikatakan bahwa amae dapat dipelajari dan diterapkan tidak hanya secara sempit, tetapi juga lebih luas.
Meskipun konsep amae masih dalam tahap pembelajaran yang lebih dalam dan lanjutan, namun amae dapat mempunyai implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena amae melibatkan hubungan antara dua pihak, maka hubungan amae dapat ditandai dengan perilaku pengambilan peran dimana satu orang adalah pencari amae atau amaera dan yang lainnya adalah penyedia amae atau amayakasu. Jadi konsep ini bisa digunakan dalam aspek hubungan interpersonal, misalnya hubungan romantis antar pasangan. Perilaku amae dapat meningkatkan kualitas hubungan ketika pencari dan penyedia dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan keintiman, seseorang yang memiliki tujuan keintiman yang tinggi cenderung lebih terlibat dalam aktivitas bersama pasangannya, memberikan dukungan sosial, dan memandang pasangannya sebagai pasangan. tujuan keintiman yang kuat dapat meningkatkan kepuasan hubungan (Sanderson & Cantor, 2001). Motivasi intim juga dikaitkan dengan emosi yang lebih positif dan budidaya yang lebih baik melalui percakapan antar pasangan (McAdams & Constantian, 1983). Menurut Marshall et al (2010), perilaku amae pada pasangan romantis mungkin dikaitkan dengan kualitas hubungan yang lebih baik dan berkurangnya konflik antar pasangan, serta peningkatan motivasi kedekatan dalam hubungan romantis.
Kita perlu meningkatkan dan menciptakan budaya perilaku amae yang universal dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya pada tataran mikro yaitu hubungan percintaan antar pasangan yang diharapkan dapat berdampak pada tataran makro dalam masyarakat yang berbudaya amae, terwujudnya emosi positif, komunikasi interpersonal yang baik, kualitas hubungan interpersonal yang baik, berkurangnya konflik secara keseluruhan, interpersonal dan intrapersonal dan keintiman yang lebih baik secara interpersonal dan intrapersonal.
Penulis: Noer Fitrianto Priyo Hutomo, Program Magister Psikologi Universitas Tarumanagara
Quoted From Many Source